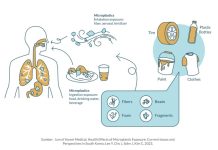Nagiot Cansalony Tambunan (Analis Kebijakan Ahli Madya dan Anggota Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) di Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan, BKPK Kemenkes RI)

Ilustrasi Foto: Dedikasi Tenaga Kesehatan‘ karya Achmad Fazeri dari Grobogan Jawa Tengah sebagai peraih Juara 1 Lomba Foto Harmoni Jawa Timur 2025. Link sumber: https://www.petrogas.co.id/juaralombafoto2025/
Pendahuluan: Kompleksitas Administrasi Negara Kepulauan
Indonesia menempati posisi yang unik sekaligus menantang dalam lanskap administrasi publik global. Berbeda dengan negara-negara kontinental yang memiliki konektivitas darat yang solid dan homogenitas demografis yang relatif tinggi, Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia. Dengan hamparan 17.000 pulau, ratusan kelompok etnis, dan variasi topografi yang ekstrem, Indonesia menyajikan tantangan disparitas yang nyata. Rentang kendali pemerintahan membentang dari pusat bisnis modern di Jakarta hingga pos kesehatan terpencil di wilayah perbatasan yang aksesibilitasnya sangat terbatas pada moda transportasi sungai atau laut.
Realitas geografis ini menciptakan tantangan asimetris dalam distribusi pelayanan publik. Apa yang mudah diakses di Jawa, sering kali menjadi barang mewah di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Dalam konteks inilah, para perumus kebijakan kesehatan dihadapkan pada ujian terberat: bagaimana menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pelayanan kesehatan yang setara kualitasnya, namun adaptif terhadap kondisi lokal.
Mandat Pembangunan: Dari Wacana Menuju Dampak Nyata
Di tengah kompleksitas tersebut, arahan strategis dari pimpinan nasional menjadi kompas navigasi birokrasi. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan visi pembangunan yang berorientasi pada hasil (outcome-based), cepat, dan delivered—artinya, setiap program pemerintah harus benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di tingkat akar rumput. Tidak ada ruang lagi bagi kebijakan yang hanya indah di atas kertas namun mandul di lapangan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menerjemahkan visi ini ke dalam transformasi kesehatan. Standar yang ditetapkan sangat tinggi: kebijakan kesehatan nasional harus mengacu pada bukti ilmiah terbaik berstandar global (global best practices). Namun, keberhasilan kebijakan tidak diukur dari seberapa canggih teknologi yang diadopsi, melainkan seberapa efektif pelayanan kesehatan tersebut menjangkau dan melindungi masyarakat di seluruh pelosok negeri secara adil dan merata.
Bagi ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya yang memegang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Anjaker) dan Administrator Kesehatan (Adminker), mandat ini adalah momentum krusial untuk melakukan transformasi kinerja. Paradigma birokrasi yang selama ini cenderung administratif dan kaku perlu diubah menjadi lebih responsif, strategis, dan berorientasi pada pemecahan masalah (problem-solving).

Ilustrasi Foto: Bidan Ilen (tengah) berada di antara para Sikerei (dukun Mentawai) saat memeriksa kondisi warga di rumah di Dusun Matektek, Desa Matotonan, Siberut Selatan, Mentawai, Sumatera Barat. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra. Link sumber: https://www.antaranews.com/berita/5114937/dua-pewarta-foto-antara-raih-juara-karya-jurnalistik-bpjs-kesehatan
Dekonstruksi Bias Urban dalam Kebijakan Publik
Tantangan terbesar dalam mewujudkan pemerataan kesehatan sering kali bersumber dari bias kognitif dalam perumusan kebijakan, atau yang sering disebut sebagai urban bias. Terdapat kecenderungan untuk melakukan generalisasi bahwa ekosistem infrastruktur dan sosial di Jakarta atau kota-kota besar lainnya merepresentasikan kondisi seluruh wilayah Indonesia.
Kekeliruan mendasar ini sering bermuara pada pendekatan kebijakan one size fits all. Kita kerap mengadopsi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau meniru kisah sukses negara maju tanpa melalui proses penyesuaian konteks (contextualization). Sebagai ilustrasi, kebijakan digitalisasi pelayanan kesehatan melalui aplikasi terintegrasi mungkin berjalan sangat efektif di Puskesmas Kecamatan Menteng, Jakarta yang didukung jaringan internet berkecepatan tinggi dan literasi digital masyarakat yang baik. Namun, kebijakan yang sama akan menghadapi kendala fundamental jika diterapkan secara mentah di Puskesmas di pedalaman Papua atau kepulauan Maluku, di mana pasokan listrik masih bergantung pada tenaga surya dan sinyal telekomunikasi masih menjadi kendala utama.
Kebijakan yang seragam di atas bentang alam yang beragam berpotensi menciptakan inefisiensi anggaran dan kegagalan program. Oleh karena itu, wawasan kebangsaan dalam perumusan kebijakan menjadi mutlak diperlukan. Mencintai Indonesia dalam konteks teknokrasi berarti memahami bahwa keadilan bukan berarti memberikan intervensi yang “sama” untuk semua, melainkan memberikan intervensi yang “sesuai” dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing daerah.
Sinergi Global dan Kearifan Lokal: Pendekatan Riset Implementasi
Untuk menjawab tantangan standardisasi di tengah keberagaman, Kementerian Kesehatan menempuh strategi kolaborasi hulu-hilir. Di tingkat global (hulu), kemitraan strategis dibangun dengan lembaga-lembaga bereputasi internasional seperti Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), Vital Strategies, dan Aceso Global. Peran mitra global ini krusial dalam menyediakan data beban penyakit (burden of disease) yang presisi, metodologi analisis mutakhir, serta referensi intervensi klinis yang telah teruji efektivitasnya di berbagai negara.
Namun, data global hanyalah bahan baku. Agar dapat diimplementasikan, bahan baku tersebut harus diolah oleh “koki” yang memahami selera lokal. Di sinilah peran institusi pendidikan dan riset lokal menjadi vital. Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes dan Universitas di seluruh Indonesia harus diberdayakan untuk melakukan Riset Implementasi (Implementation Research).
Fokus riset implementasi bukan lagi pada pertanyaan “apa obatnya?”, karena hal tersebut sudah dijawab oleh standar medis global. Pertanyaan kuncinya bergeser menjadi “bagaimana agar pengobatan ini dapat diterima, diakses, dan dipatuhi oleh masyarakat setempat?”. Riset ini menggali aspek antropologis, sosiologis, dan logistik lokal. Sinergi antara akurasi data standar dunia dan jejaring akademisi lokal yang memahami medan adalah kunci untuk memastikan kebijakan tidak hanya sahih secara ilmiah, tetapi juga operasional di lapangan.
Transformasi Peran Anjaker: Dari Administrator Menjadi Knowledge Broker
Perubahan lanskap kebijakan ini menuntut redefinisi peran Anjaker. Rekan-rekan Anjaker tidak boleh lagi terjebak hanya sebagai penyusun rekomendasi kebijakan atau draf regulasi secara administratif. Anjaker harus bertransformasi menjadi Knowledge Broker—perantara pengetahuan yang andal.
Seorang Anjaker harus memiliki kemampuan untuk mensintesis data global yang kompleks, memadukannya dengan temuan riset implementasi lokal, lalu merumuskannya menjadi opsi kebijakan yang asimetris. Artinya, Anjaker harus berani menyodorkan rekomendasi kebijakan yang variatif: satu set rekomendasi untuk daerah perkotaan dengan infrastruktur mapan, dan set rekomendasi lain untuk daerah kepulauan atau pedalaman. Kemampuan untuk merancang kebijakan yang fleksibel namun tetap dalam koridor standar mutu adalah kompetensi inti yang dibutuhkan saat ini.
Transformasi Peran Adminker: Menjadi Penerjemah Kultural
Setali tiga uang, rekan-rekan Adminker juga memegang peran strategis sebagai “Penerjemah Kultural” sistem kesehatan. Saat ini, jabatan Adminker diisi oleh talenta dengan beragam latar belakang teknis, mulai dari epidemiologi, kesehatan lingkungan, hingga promosi kesehatan.
Keahlian teknis spesifik ini tidak boleh terpinggirkan oleh rutinitas administratif. Justru, perspektif teknis inilah yang menjadi nilai tambah. Seorang Adminker berlatar belakang sanitarian, misalnya, memiliki kepekaan untuk menilai apakah standar sanitasi rumah sakit global dapat diterapkan di wilayah pasang surut air laut. Seorang epidemiolog memahami nuansa pelacakan kontak penyakit menular di tengah pasar tradisional yang padat. Kepekaan kontekstual ini sangat esensial untuk memberikan masukan kepada pimpinan agar layanan yang diminta Presiden dapat memperkuat, bukan membenturkan, kearifan lokal.
Penutup: Menuju Birokrasi Berbasis Evidence-Based Pragmatism
Kita kini memasuki era pragmatisme berbasis bukti (evidence-based pragmatism). Tantangan geografis dan keragaman budaya tidak boleh lagi dijadikan alasan pembenar atas lambatnya pelayanan publik. Sebaliknya, keragaman tersebut harus menjadi katalis bagi kreativitas birokrasi untuk menciptakan inovasi layanan.
Kita membutuhkan arsitektur kebijakan yang luwes: sistem yang serba digital untuk smart city, namun tetap humanis dan manual untuk wilayah blank spot; pengobatan yang canggih secara medis, namun disampaikan dengan pendekatan yang santun secara budaya.
Kepada seluruh Anjaker dan Adminker, tugas kita adalah mengoptimalkan data global demi kedaulatan kesehatan nasional. Mari kita tinggalkan ruang kerja kita sejenak, turun ke lapangan bersama para peneliti, dan mendengar aspirasi serta kebutuhan riil masyarakat. Hanya dengan pendekatan yang membumi, kita dapat memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara dikonversi menjadi manfaat nyata bagi peningkatan derajat kesehatan rakyat Indonesia. Kebijakan yang efektif dan bermartabat adalah kebijakan yang menghormati kondisi geografis dan sosiologis warganya.